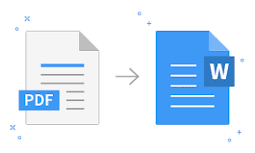PENGANTAR
Pada tahun 1811 Prancis menjajah
Belanda dan memberlakukan Code Penal (kodifikasi hukum pidana) yang
dibuat tahun 1810 saat Napoleon Bonaparte menjadi penguasa Prancis. Pada tahun
1813 Prancis meninggalkan negeri Belanda, namun demikian negeri Belanda masih
mempertahankan Code Penal tersebut sampai tahun 1886. Pada
tahun 1886 mulai diberlakukan Wetboek van Strafrecht sebagai
pengganti Code Penal Napoleon.
Setelah Indonesia menyatakan
kemerdekaannya pada tahun 1945 untuk mengisi kekosongan hukum pidana yang
diberlakukan di Indonesia maka atas dasar pasal II Aturan Peralihan UUD
1945, WvSNI tetap diberlakukan. Pemberlakuan WvSNI menjadi
hukum pidana Indonesia ini menggunkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang
Peraturan Hukum Pidana Indonesia. Dalam pasal VI Undang-undang Nomor 1 Tahun
1946 disebutkan bahwa nama Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch
Indie diubah menjadi Wetboek van Strafrecht dan
“dapat disebut sebagai Kitab Undang-undang Hukum Pidana”. Disamping itu,
Undang-undang ini juga tidak memberlakukan kembali peraturan-peraturan pidana
yang dikeluarkan sejak tanggal 8 Maret 1942 baik yang dikeluarkan oleh
pemerintah Jepang maupun oleh panglima tertinggi Balatentara Hindia Belanda.
Oleh karena perjuangan bangsa
Indonesia belum selesai pada tahun 1946 dan munculnya dualisme KUHP setelah
tahun tersebut, maka pada tahun 1958 dikeluarkan Undang-undang Nomor 73 Tahun
1958 yang memberlakukan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 bagi seluruh wilayah
Republik Indonesia. Saat ini, KUHP telah berlaku kurang lebih selama 72 Tahun.
Banyak undang-undang khusus yang telah dibuat dalam rangka mengcover kekurangan
yang ada pada KUHP, bahkan sampai upaya untuk melakukan pembharuan KUHP.
Pembaharuan hukum pidana pada
hakekatnya merupakan suatu upaya melakukan peninjauan dan pembentukan kembali
hukum pidana yang sesuai dengan nilai-nilai sentral sosio-politik,
sosio-filosofik dan nilai-nilai sosio-kultural masyarakat Indonesia. Oleh
karena itu, penggalian nilai-nilai yang ada dalam bangsa Indonesia dalam usaha
pembaharuan hukum pidana Indonesia harus dilakukan agar hukum pidana Indonesia
masa depan sesuai dengan sosio-politik, sosio filosofik, dan nilai-nilai
sosio-kultural masyarakat Indonesia. Pada pelakasanaanya penggalian nilai ini
bersumber pada hukum adat, hukum pidana positif (KUHP), hukum agama, hukum
pidana negara lain, serta kesepakatan-kesepakatan internasional mengenai materi
hukum pidana.
Adapun alasan-alasan yang mendasari perlunya pembaharuan hukum pidana
nasional pernah diungkapkan oleh Sudarto, yaitu:
a.
Alasan yang bersifat politik, yakni bahwa negara Republik Indonesia yang
merdeka memiliki KUHP yang bersifat nasional, yang dihasilkan sendiri. Ini
merupakan kebanggaan nasional yang inherent dengan kedudukan sebagai negara
yang telah melepaskan diri dari penjajahan. Oleh karena itu, tugas dari
pembentuk undang-undang adalah menasionalkan semua peraturan perundang-undangan
warisan kolonial, dan ini harus didasarkan kepada Pancasila sebagai sumber dari
segala sumber hukum.
b.
alasan yang bersifat sosiologis bahwa pencerminan dari nilai-nilai
kebudayaan dari suatu bangsa, karena ia memuat perbuatan-perbuatan yang tidak
dikehendaki dan mengikatkan pada perbuatan-perbuatan itu suatu sanksi yang
bersifat negatif berupa pidana. Ukuran untuk menentukan perbuatan mana yang
dilarang itu tentunya bergantung pada pandangan kolektif yang terdapat dalam
masyarakat tentang apa yang baik, yang benar dan sebaliknya.
c.
Alasan yang bersifat praktis, yakni bahwa
teks resmi WvS adalah berbahasa Belanda meskipun menurut Undang-undang
Nomor 1 Tahun 1946 dapat disebut secara resmi sebagai KUHP. Dapat diperhatikan
bahwa jumlah penegak hukum yang memahami bahasa asing semakin sedikit. Di lain
pihak, terdapat berbagai ragam terjemahan KUHP yang beredar. Sehingga dapat
dimungkinkan akan terjadi penafsiran yang menyimpang dari teks aslinya yang
disebabkan karena terjemahan yang kurang tepat.
Berdasarkan beberapa pertimbangan tersebut di atas, maka telah dilakukan
perumusan rancangan Pembharuan KUHP yang terakhir kali dilakukan pada tahun
2017. Namun demikian, dalam beberapa diskusi baik pada media televise maupun
diskusi ilmiah, masih terdapat perdebatan diantara kalangan praktisi dan
akademisi. Dalam penullisan makalah ini penulis mencoba mengkaji ketentuan
Pasal 91, 92, 93, 94, 95, 96 dan 97 dalam rancangan KUHP yang juga masih menuai
perdebatan.
Analisis
Pasal 91 dan Pasal 92 R-KUHP (Pidana Tambahan berupa Pencabutan Kekuasaan
Terhadap Anak)
Dalam ketentuan rancangan KUHP edisi tahun 2017, disebutkan bahwa:
Kekuasaan bapak, wali, wali pengawas,
pengampu, dan pengampu pengawas, baik atas anaknya sendiri maupun atas anak
orang lain, dapat dicabut jika yang bersangkutan dipidana karena:
a.
dengan sengaja melakukan tindak pidana bersama-sama dengan anak
yang belum cukup umur yang berada dalam kekuasaannya; atau
b.
melakukan tindak pidana terhadap anak yang belum cukup umur yang
berada dalam kekuasaannya sebagaimana dimaksud dalam Buku Kedua.
Selanjutnya, Rancangan Pasal 92 menentukan bahwa:
(1) Jika pidana pencabutan hak dijatuhkan maka
wajib ditentukan lamanya pencabutan sebagai berikut:
a.
dalam hal dijatuhkan pidana mati atau pidana seumur hidup, pencabutan hak
untuk selamanya;
b.
Dalam hal dijatuhkan pidana penjara, pidana tutupan, atau pidana pengawasan
untuk waktu tertentu, pencabutan hak paling singkat 2 (dua) tahun dan paling
lama 5 (lima) tahun lebih lama dari pidana pokok yang dijatuhkan; atau
c.
Dalam hal pidana denda, pencabutan hak paling singkat 2 (dua) tahun dan
paling lama 5 (lima) tahun.
(2) Pidana pencabutan hak mulai berlaku pada
tanggal putusan hakim dapat dilaksanakan.
Pengaturan pasal ini, bukan merupakan hal yang baru. Dalam Undang-Undang
Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002
tentang Perlindungan Anak, disebutkan bahwa:
Pasal 26
(3) Orang tua berkewajiban dan bertanggung
jawab untuk :
a.
mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;
b.
menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; dan
c.
mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.
(4) Dalam hal orang tua tidak ada, atau tidak
diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab, tidak dapat melaksanakan
kewajiban dan tanggung jawabnya, maka kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) dapat beralih kepada keluarga, yang dilaksanakan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.
Selanjutnya, ketentuan Pasal 30 menentukan bahwa:
Pasal 30
(1)
Dalam hal orang tua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, melalaikan
kewajibannya, terhadapnya dapat dilakukan tindakan pengawasan atau kuasa asuh
orang tua dapat dicabut.
(2)
Tindakan pengawasan terhadap orang tua atau pencabutan kuasa asuh
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui penetapan pengadilan.
Perihal kekuasaan orang tua terhadap anak, juga dibahas lebih mendalam
dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Menurut
pasal 45 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa:
(1) Kedua orang tua wajib memelihara dan
mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya
(2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam
ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri
kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.
Dalam hal demikian, kekuasaan tersebut dapat dicabut apabila ada
alasan-alasan yang kuat akan pencabutan tersebut. Sebagaimana dijelaskan dalam
pasal 49 Undang-Undang Perkawinan:
(1)
Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasannya terhadap
seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua
yang lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan saudara kandung yang
telah dewasa atau pejabat yang berwenang dengan keputusan Pengadilan dalam
hal-hal:
a.
Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya
b.
Ia berkelakuan buruk sekali
(2)
Meskipun orang tua dicabut kekuasaannya, mereka masih tetap berkewajiban
untuk memberi biaya pemeliharaan kepada anak tersebut.
Dengan adanya pengaturan pada Undang-Undang Perlindungan anak dan
Undang-Undang Perkawinan, penulis berpendapat bahwa, pengaturan tentang
pencabutan kekuasaan orang tua pada Pasal 91, tidak perlu lagi dimasukkan ke
dalan KUHP. Hal ini dikarenakan, pengaturan yang sudah ada tersebut merupakan
pengaturan yang bersifat khusus, sehingga meskipun KUHP yang baru nantinya
mengatur hal yang sama, maka yang akan digunakan tetap pengaturan yang diatur
pada undang-undag Khusus. Hal ini didasarkan pada asas hukum pidana yakni Lex specialis derogat legi generali yang
merupakan asas penafsiran hukum bahwa hukum yang bersifat khusus (lex specialis) mengesampingkan hukum
yang bersifat umum (lex generalis).
Pasal
93, 94, dan 95 R-KUHP (Pidana Tambahan berupa Perampasan Barang)
Pasal 93 R-KUHP mennjelaskan bahwa:
(1) Pidana perampasan barang dan/atau tagihan
tertentu dapat dijatuhkan tanpa pidana pokok jika ancaman pidana penjara
terhadap tindak pidana yang bersangkutan tidak lebih dari 7 (tujuh) tahun.
(2) Pidana perampasan barang tertentu dan/atau
tagihan dapat juga dijatuhkan, jika terpidana hanya dikenakan tindakan.
(3) Pidana perampasan barang yang bukan milik
terpidana tidak dapat dijatuhkan, jika hak pihak ketiga dengan itikad baik akan
terganggu.
Pasal 94 R-KUHP
menjelaskan bahwa:
Barang yang
dapat dirampas adalah:
a.
barang yang dipergunakan untuk mewujudkan atau mempersiapkan tindak pidana;
b.
barang yang khusus dibuat atau diperuntukkan untuk mewujudkan tindak
pidana;
c.
barang yang ada hubungan dengan terwujudnya tindak pidana;
d.
barang dan/atau tagihan milik terpidana atau orang lain yang diperoleh dari
tindak pidana;
e.
keuntungan ekonomi apapun yang diperoleh baik secara langsung maupun tidak
langsung dari tindak pidana; dan/atau
f.
barang yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana.
Pasal 95 R-KUHP
menjelaskan bahwa:
(1) Pidana perampasan dapat dijatuhkan atas
barang yang tidak disita, dengan menentukan barang tersebut harus diserahkan
atau diganti dengan sejumlah uang menurut taksiran hakim.
(2) Jika barang yang disita tidak dapat
diserahkan maka dapat diganti dengan sejumlah uang menurut taksiran hakim
sesuai dengan harga pasar.
(3) Jika terpidana tidak mampu membayar
seluruh atau sebagian harga pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat
(2) maka berlaku ketentuan pidana pengganti untuk pidana denda.
Pidana tambahan menurut Andi Hamzah, adalah pidana yang hanya dapat
dijatuhkan di samping pidana pokok. Penjatuhan pidana tambahan sifatnya
fakultatif namun menjatuhkan pidana tambahan tidak boleh tanpa dengan menjatuhkan
pidana pokok, sehingga harus bersama-sama. Pidana tambahan menurut Marjane Termorshuizen dalam Kamus Hukum
Belanda Indonesia, dalam Bahasa Belanda disebut dengan bijkomende staf adalah pidana yang hanya dapat dijatuhkan di
samping pidana pokok. [1]
Jenis pidana tambahan yaitu terdiri dari pencabutan beberapa hak tertentu,
perampasan barang tertentu, pengumuman putusan hakim (lihat ketentuan dalam
Pasal 10 KUHP).[2]
1)
Pidana pencabutan hak-hak tertentu menurut Pasal 35 ayat (1) KUHP, adalah
pencabutan seluruh hak yang dimiliki seseorang yang dapat mengakibatkan
kematian perdata tidak diperkenankan. Hak-hak yang dicabut adalah sebagai berikut:
(1)
hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan yang tertentu;
(2)
hak menjalankan jabatan dalam angkatan bersenjata/TNI;
(3)
hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan
aturan-aturan umum;
(4)
hak menjadi penasehat hukum atau pengurus atas penetapan pengadilan, hak
menjadi wali, wali pengawas, pengampu, atau pengampu pengawas atas anak yang
bukan anak sendiri;
(5)
hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian atau pengampuan atas
anak sendiri;
(6)
hak menjalankan mata pencaharian.
2)
Pidana perampasan barang tertentu menurut Adami chazawi, adalah hukuman
perampasan barang sebagai satu pidana
hanya diperkenankan atas barang-barang tertentu saja, tidak untuk semua barang.
Ada dua jenis barang yang dapat dirampas melalui putusan hakim pidana, yaitu:
a)
barang-barang yang berasal /diperoleh dari suatu kejahatan (bukan dari
pelanggaran), menurut Marjane Termorshuizen dalam Kamus Hukum Belanda
Indonesia, dalam bahasa Belanda adalah corpora delictie yang berarti barang
bukti, misalnya uang palsu dari kejahatan pemalsuan uang, surat cek palsu dari
kejahatan pemalsuan surat;
b)
barang-barang yang digunakan dalam melakukan kejahatan, menurut Marjane
Termorshuizen dalam Kamus Hukum Belanda Indonesia, dalam bahasa Belanda adalah instrumental delictie, yang berarti
sarana dengan mana kejahatan dilakukan, sarana terlaksananya kejahatan,
misalnya pisau yang digunakan dalam kejahatan pembunuhan atau penganiayaan,
anak kunci palsu yang digunakan dalam pencurian dan sebagainya.
Melihat ketentuan tersebut di atas, maka
penulis penyimpulkan bahwa pengaturan pada Pasal 93, 94, dan 95 R-KUHP memuat
pengaturan yang lebih luas dan eksplisit dalam menentukan kategori barang yang
dapat dirampas. Hal ini merupakan pengaturan yang baik, mengingat bahwa
perkembangan tentang kejahatan semakin canggih, khususnya yang berkaitan dengan
penggunaan barang yang berkaitan dengan perwujudan suatu kejahatan. Oleh karena
itu, penulis memandang pengaturan tersebut penting untuk tetap dipertahankan
sebagai salah satu bentuk pidana tambahan.
Pasal
96 dan 97 R-KUHP (Pidana Tambahan berupa Pengumuman Putusan Hakim)
Pasal 96 R-KUHP menegaskan bahwa:
(1) Jika dalam putusan hakim diperintahkan
supaya putusan diumumkan maka harus ditetapkan cara melaksanakan pengumuman
tersebut dengan biaya yang ditanggung oleh terpidana.
(2) Jika biaya pengumuman sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) tidak dibayar oleh terpidana maka berlaku ketentuan pidana
pengganti untuk pidana denda.
Pasal 97 R-KUHP menegaskan bahwa:
(1) Dalam putusan hakim dapat ditetapkan
kewajiban terpidana untuk melaksanakan pembayaran ganti kerugian kepada korban
atau ahli warisnya.
(2) Jika kewajiban pembayaran ganti kerugian
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan maka berlaku ketentuan
pidana pengganti untuk pidana denda.
Pidana pengumuman putusan hakim menurut Adamichazawi, adalah pidana
pengumuman putusan hakim yang hanya dapat dijatuhkan dalam hal-hal yang telah
ditentukan dalam undang-undang, misalnya terdapat dalam Pasal 128 ayat (3)
KUHP, Pasal 206 ayat (2) KUHP, Pasal 361 KUHP, Pasal 377 ayat (1) KUHP, Pasal
395 ayat (1) KUHP, Pasal 405 ayat (2) KUHP. Setiap putusan hakim memang harus
diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum bila tidak putusan batal
demi hukum, sesuai ketentuan Pasal 195 KUHAP yang tertulis bahwa “Semua putusan
pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan di sidang
terbuka untuk umum. Pidana pengumuman putusan hakim ini merupakan suatu
publikasi ekstra dari suat putusan pemidanaan seseorang dari pengadilan pidana.
Dalam pengumuman putusan hakim ini, hakim bebas menentukan perihal cara
melaksanakan pengumuman itu. Maksud dari pengumuman putusan hakim yang demikian
ini adalah sebagai usaha preventif mencegah bagi orang-orang tertentu, agar
tidak melakukan tindakan pidana yang sering dilakukan orang. Maksud lain adalah
memberitahukan kepada masyarakat umum agar berhati-hati dalam bergaul dan
berhubungan dengan orang-orang yang dapat disangka tidak jujur, sehingga tidak
menjadi korban dari kejahatan.
Pengaturan tentang pidana tambahan berupa pengumuman putusan hakim pada
Rancangan KUHP merupakan suatu hal yang positif. Hal ini dikarenakan pada
pengaturan tersebut, diatur mengenai tata cara pengumuman dan penanggung biaya
pengumuman putusan yang disertai dengan pidana pengganti. Hal ini sangat
mendukung proses penjeraan bagi seorang terpidana, serta pengumuman putusan hakim juga seyogyanya
dapat mencegah terjadinya tidak pidana di masyarakat.
DAFTAR PUSTAKA
A. Hamzah, 2002, Hukum Acara Pidana Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta.
Chazawi , Adami, 2002 Pelajaran Hukum Pidana (Bagian I), P.T.Radja Grafindo
Persada Makassar.
Dirjosisworo Soedjono, 1994, Hukuman dalam Perkembangan Hukum Pidana
Tarsito, Bandung.
Muladi dan Barda Nawawi Arif, 1984. Teori-Teori Kebijakan Pidana, Alumni,
Bandung.
Sholehuddin, 2002, Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana (Ide Dasar Double Track
System & Implementasinya). P.T.Radja Grafindo Persada,Jakarta
[1] A. Hamzah, 2002, Hukum Acara Pidana Indonesia, Sinar Grafika,
Jakarta. Hal. 121.
[2] Chazawi , Adami, 2002 Pelajaran Hukum Pidana (Bagian I), P.T.Radja
Grafindo Persada Makassar. Hal. 44-45.